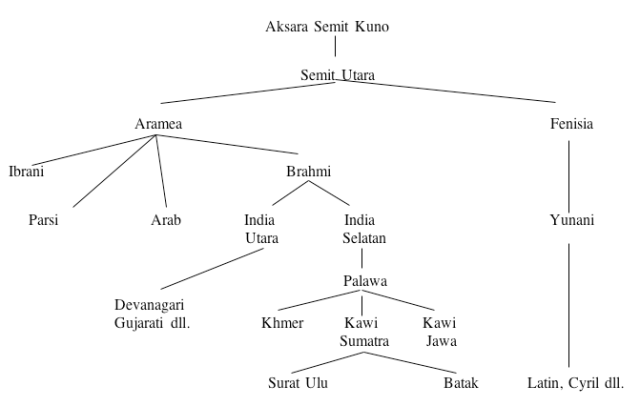DENOMINASI RUPIAH
Isu
denominasi rupiah yang beredar belakangan ini cukup menarik perhatian
masyarakat. Keresahan cukup wajar karena masyarakat teringat pemotongan
nilai uang dizaman Bung Karno (1959) dimana inflasi mencapai 635,5%!.
Lebih banyak tanggapan kuatir akan dampak ‘pemotongan’ nilai rupiah,
terutama bagi kalangan masyarakat kecil.
PENGERTIAN DENOMINASI
Denominasi
adalah menyederhanakan pecahan mata uang menjadi pecahan lebih sedikit
dengan cara mengurangi digit angka nol tanpa mengurangi nilai mata uang
tersebut.
Rencana pemerintah RI untuk Denominasi rupiah
dikawatirkan akan menjadi masalah bagi sistematis ekonomi apabila
sosialisasi pemerintah yang tidak tepat. Bank Indonesia harus
benar-benar siap dalam melakukan Denominasi rupiah ini, BI membutuhkan
sosialiasi yang luar biasa agar semua masyarakat paham. Padahal,
masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan ekonomi dan
pendidikan.
Denominasi
yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah pengurangan 3 digit. Uang
Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) jika didenominasi menjadi Rp.10 (sepuluh
rupiah) . Banyak masyarakat yang menghawatirkan jika Denominasi
dilakukan ditakutkan masyarakat malah akan khawatir nilai uangnya
terpotong, dan padahal tidak. Nantinya, orang akan beramai-ramai
menukarkan rupiah ke dolar, karena pemerintah AS menjamin dolar yang
telah dikeluarkan tidak akan diganti dan dikurangi.
Kabarnya Denominasi akan bisa berjalan pada tahun 2015 mendatang, yang jadi pertanyaan apakah pemerintah benar-benar siap dalam mempersiapkan dan mensosialisasikan Redenominasi ini kepada masyarakat Indonesia? Lalu bagaimana nanti ketika uang 1.000 menjadi 1 rupiah dan masyarakat yang belanja di supermarket ketika mendapatkan uang kembali yang biasanya diganti permen.
Kabarnya Denominasi akan bisa berjalan pada tahun 2015 mendatang, yang jadi pertanyaan apakah pemerintah benar-benar siap dalam mempersiapkan dan mensosialisasikan Redenominasi ini kepada masyarakat Indonesia? Lalu bagaimana nanti ketika uang 1.000 menjadi 1 rupiah dan masyarakat yang belanja di supermarket ketika mendapatkan uang kembali yang biasanya diganti permen.
PRO KONTRA DENOMINASI
Wacana
Bank Indonesia (BI) menyederhanakan pecahan mata uang (denominasi)
rupiah harus disertai sosialisasi masif kepada seluruh lapisan
masyarakat.
BI
dan pemerintah diminta tidak ceroboh mengabaikan dampak sosial dan
psikologis apabila kebijakan itu diberlakukan tanpa sosialisasi yang
memadai. Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas),
Sigit Pramono, mengingatkan pemerintah dan BI bahwa pemahaman masyarakat
Indonesia terhadap masalah-masalah perekonomian maupun keuangan sangat
beragam.
Artinya,
kebijakan perekonomian yang berdampak luas kepada masyarakat sebaiknya
dipersiapkan dan disosialisasikan secara baik. “Harus ada koordinasi
antara pemerintah, BI, dan seluruh pemangku kepentingan terkait
kebijakan ini.Hal yang paling penting sosialisasi harus meluas dan
mendalam,” ujarnya saat dihubungi Seputar Indonesia di Jakarta kemarin.
Seperti
diberitakan, BI menggulirkan wacana untuk melakukan penyederhanaan
pecahan mata uang rupiah. Bank sentral beralasan, uang pecahan terbesar
Indonesia, Rp100.000, merupakan yang terbesar kedua di dunia, setelah
Vietnam dengan pecahan terbesar 500.000 dong. Bila memperhitungkan
Zimbabwe,yang pernah mencetak pecahan 100 miliar dolar,pecahan Rp100.000
menempati urutan ketiga terbesar.
Kita
ingat kembali bahwa Denominasi adalah menyederhanakan (pecahan) mata
uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka
nol) tanpa memangkas nilai mata uang tersebut. Semisal terjadi
denominasi tiga digit (3 angka 0), maka Rp1.000 menjadi Rp1. Nantinya
pecahan mata Rp1 baru setara dengan denominasi Rp1.000 yang lama. Sigit
Pramono menuturkan, Perbanas pada prinsipnya mendukung denominasi
lantaran akan meningkatkan efisiensi transaksi dan pembukuan.
Syaratnya,
pemerintah dan BI berhati-hati sebelum memberlakukan kebijakan
tersebut. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sandiaga Uno berharap
masyarakat tidak menyikapi wacana denominasi dengan
berlebihan.Denominasi merupakan ide bagus yang akan mempermudah
transaksi. “Yang penting sekarang sosialisasi harus dilakukan dengan
matang, baik tentang arti maupun tujuan denominasi,” paparnya.
Menteri
Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menegaskan bahwa wacana denominasi
rupiah masih merupakan kajian BI, belum merupakan keputusan resmi.
Pemerintah belum membahas secara khusus kajian BI tersebut. ”Ada satu
studi yang dilakukan BI, itu belum final,kami di pemerintah belum
dikonsultasikan (oleh BI mengenai) hal itu.Jadi kami belum bisa bilang
apa-apa.
Itu
masih lama dan masih studi,”ujarnya. Berdasarkan studi yang dilakukan
BI, denominasi tidak akan berdampak buruk bagi perekonomian. Walau
begitu pemerintah belum bisa menanggapi implementasi wacana itu.
Lantaran sifatnya kajian, belum tentu denominasi akan dilaksanakan
menjadi sebuah kebijakan.
Butuh Biaya Besar
Kalangan
bankir berpendapat implementasi denominasi butuh biaya besar. Perbankan
perlu menyesuaikan sistem teknologi informasi apabila denominasi
benar-benar diimplementasikan. “Kebijakan itu justru hanya akan
meningkatkan biaya operasional, terutama masalah teknologi informasi.
Belum lagi masalah yang timbul akibat kesalahan manusia,” ujar Direktur
Utama Bank Agro Kemas M Arief.
Selain
itu, yang tidak bisa diduga adalah kemungkinan reaksi masyarakat yang
berlebihan. “Apalagi urgensi melakukan denominasi ini juga belum
jelas,”ungkap Kemas. Direktur Konsumer BII Stephen Liestyo mengatakan,
sistem komputerisasi perbankan harus diubah apabila denominasi
dijalankan. Alasannya, dalam masa transisi ada dua mata uang yang
berlaku, yakni rupiah lama dan rupiah baru.
“Sehingga
perbankan harus mengubah komputerisasi untuk mengakomodasi hal
tersebut,” kata Stephen. Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja
menilai denominasi akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dari
sisi positif, denominasi akan menjadikan pecahan mata uang lebih
sederhana. Negatifnya, kebijakan itu butuh biaya, terutama untuk
pengaturan sistem dan penyesuaian materi cetak.
”Kalau
diyakini positifnya akan baik untuk negara kita dalam jangka panjang,
kita akan konsekuen menjalankannya,” kata Parwati. Country Business
Manager Citi Indonesia Tigoor M Siahaan menjelaskan, redenominasi akan
menghabiskan biaya besar, baik dari BI sendiri maupun dari kalangan
perbankan. Karena itu, dia berharap BI segera membuat program
sosialisasi wacana itu secepatnya agar tidak menimbulkan kepanikan.
“Kebijakan
itu tentu akan memakan biaya besar, terutama BI yang harus melakukan
pencetakan uang kembali. Tapi bagi kami juga besar karena harus
menyiapkan segala infrastrukturnya,” tambah Tigoor. Direktur Utama Bank
Bukopin Glen Glenardi berharap BI mewaspadai dampak sosial yang akan
terjadi setelah kebijakan itu diterapkan. Dia mengkhawatirkan trauma
masyarakat pada kebijakan sanering pada 1966.
”Saya
khawatir persepsi masyarakat seperti pada saat Orde Lama,sehingga
mereka tidak percaya pada rupiah,”kata Glen. Direktur Utama Bursa Efek
Indonesia (BEI) Ito Warsito mengatakan, wacana redenominasi tidak akan
berdampak besar bagi pasar modal.Wacana itu bukan isu penting yang
memicu kekhawatiran pelaku pasar. “Kepanikan itu hanya investor
individu,”ujar Ito. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita
Wiryawan menyambut positif wacana denominasi.
“Tidak
masalah, justru (uang) akan lebih mudah dibawanya,”kata dia. Adapun
dari sisi investasi,denominasi tidak akan memberi imbas negatif terhadap
investasi asing yang masuk ke Indonesia.Sebab,denominasi tidak
mengurangi nilai mata uang dalam negeri. Menurut dia, hal yang perlu
mendapat perhatian, yakni saat praktiknya kelak. Diaberharap, jika
denominasi diterapkan, bisa berjalan dalam batas wajar dan sesuai dengan
aturan yang berlaku.
Menteri
Perindustrian MS Hidayat beranggapan, penerapan redenominasi justru
perlu dilakukan lantaran nominal mata uang Indonesia terbilang besar.
“Di dunia, hanya kita (Indonesia) dan Vietnam yang nominasi mata uangnya
besar,”ujarnya. Hidayat berpandangan,denominasi tidak akan memberikan
pengaruh buruk terhadap sektor industri. Pelaku industri akan mudah
menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Namun dia meminta
sosialisasi denominasi dilakukan dengan benar agar tidak mengagetkan
kalangan industri ketika kebijakan tersebut direalisasikan.
Fokus Inflasi
Anggota
Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Nusron Wahid berharap Gubernur BI
tidak lagi menggulirkan wacana kontraproduktif seperti
denominasi.Seharusnya BI lebih fokus mengurusi tugas pokoknya, yaitu
mengendalikan stabilitas moneter (inflasi) dan nilai tukar serta
mendorong intermediasi perbankan. “Kalau redenominasi ini sebaiknya
didiskusikan di internal dulu.
Jika
situasinya sudah tepat, baru dikeluarkan,” katanya. Menurut anggota
Komisi XI dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait,denominasi seharusnya bukan
menjadi prioritas BI saat ini. Dia meminta Gubernur BI terpilih Darmin
Nasution fokus terhadap sembilan catatan yang telah direkomendasikan DPR
sebelumnya. “Itu (denominasi) bukan jadi prioritas Darmin kali ini.
Sebaiknya Darmin fokus pada sembilan catatan yang telah kami berikan
sebelumnya, saat pemilihan (gubernur BI),”ungkap Maruarar.
Sembilan
catatan itu antara lain menurunkan suku bunga pinjaman, mengatasi
dominasi perbankan asing, pengaturan hot money, asas resiprokal,
mengendalikan moneter dan meningkatkan intermediasi perbankan. Sembilan
catatan itu sudah menjadi komitmen bersama antara DPR dan Gubernur BI
terpilih dan harus diwujudkan dalam bentuk peta kebijakan (roadmap) yang
pro pada sektor riil. “Seharusnya Darmin fokus terhadap sembilan
catatan yang kami minta, bukan membuat kebijakan lain,”tegasnya.
Penjelasan Guberbur BI terkait masalah Denominasi :
Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution, menegaskan bahwa denominasi rupiah bukanlah sanering atau pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang.
Denominasi sama
sekali tidak merugikan masyarakat karena berbeda dengan sanering atau
pemotongan. Dalam denominasi nilai uang terhadap barang tidak akan
berubah, yang terjadi hanya penyederhanaan dalam nilai nominalnya berupa
penghilangan beberapa digit angka nol,” jelas Darmin kepada Antaranews
di Jakarta.
Darmin mengemukakan, denominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju ke arah yang lebih sehat, sedangkan sanering adalah pemotongan nilai mata uang dalam kondisi perekonomian yang tidak sehat, yaitu dengan memotong nilai uangnya saja.
Dalam denominasi,
baik nilai uang maupun barang, hanya dihilangkan beberapa angka nolnya
saja. Dengan demikian,denominasi akan menyederhanakan penulisan nilai
barang dan jasa yang diikuti pula penyederhanaan penulisan alat
pembayaran,” ujarnya.
Menurut Darmin, denominasi akan menyederhanakan sistem akuntasi dalam sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.
BI belum akan menerapkan denominasi dalam
waktu dekat ini karena BI menyadari bahwa denominasi membutuhkan
komitmen nasional serta waktu dan persiapan yang cukup panjang,”katanya.
Dalam
tahapan riset mengenai denominasi, BI akan secara aktif melakukan
diskusi dengan berbagai pihak untuk mencari masukan dan hasilnya akan
diserahkan pada pihak-pihak terkait agar dapat menjadi komitmen
nasional.
Darmin mengatakan, keberhasilan
denominasi akan sangat ditentukan oleh berbagai hal yang saat ini
tengah dikaji sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa negara yang
telah sukses menerapkannya.
Beberapa
faktor yang mendukung suksesnya pelaksanaan denominasi adalah
ekspektasi inflasi yang berada pada kisaran rendah dengan pergerakan
yang stabil, stabilitas perekonomian yang terjaga serta adanya jaminan
terhadap stabilitas harga serta adanya kebutuhan dan kesiapan
masyarakat.
Adapun Tahapan Rencana Bank Indonesia Redenominasi Rupiah
Tahun 2012-2013
Pada tahun-tahun tersebut dilakukan sosialisasi.
Pada tahun-tahun tersebut dilakukan sosialisasi.
Tahun 2013-2015
Merupakan masa transisi. Pada masa transisi digunakan dua rupiah, yakni memakai istilah rupiah lama dan rupiah hasil denominasi yang disebut rupiah baru.
Dalam masa transisi ini akan ada dua quotasi penyebutan nominal uang.
Pada masa ini masyarakat juga bisa menggunakan dua jenis mata uang. Misalnya, ada pembeli dengan uang baru, si penjual bisa memberi kembalian dengan uang baru maupun uang lama, ataupun campuran keduanya. Toko yang menjual barang wajib memasang dua label harga, yakni harga barang lama dan baru.
Pada masa transisi itu juga, BI akan mencetak uang baru yang diredenominasi. Sebagai contoh, BI akan mencetak Uang Rp 10,- yang akan menggantikan Rp 10.000,-.
Merupakan masa transisi. Pada masa transisi digunakan dua rupiah, yakni memakai istilah rupiah lama dan rupiah hasil denominasi yang disebut rupiah baru.
Dalam masa transisi ini akan ada dua quotasi penyebutan nominal uang.
Pada masa ini masyarakat juga bisa menggunakan dua jenis mata uang. Misalnya, ada pembeli dengan uang baru, si penjual bisa memberi kembalian dengan uang baru maupun uang lama, ataupun campuran keduanya. Toko yang menjual barang wajib memasang dua label harga, yakni harga barang lama dan baru.
Pada masa transisi itu juga, BI akan mencetak uang baru yang diredenominasi. Sebagai contoh, BI akan mencetak Uang Rp 10,- yang akan menggantikan Rp 10.000,-.
Tahun 2016-2018
Proses penarikan uang lama dilakukan.
Proses penarikan uang lama dilakukan.
Tahun 2019-2020
Keterangan ‘baru’ dalam uang denominasi akan dihapus dan sejak saat itu semua masyarakat akan melakukan transaksi jual beli dengan uang baru yang telah didenominasi.
Keterangan ‘baru’ dalam uang denominasi akan dihapus dan sejak saat itu semua masyarakat akan melakukan transaksi jual beli dengan uang baru yang telah didenominasi.
Kekhawatiran Masyarakat dengan Denominasi mata uang rupiah,
sebenarnya masuk akal terutama bagi orang kaya yang memiliki uang
milyaran rupiah, misal Rp. 1.000.000.000,- yang tadinya jumlah nol (0)
nya sembilan (9) bersisa enam (6) saja yaitu Sejuta saja Rp.
1.000.000,-, jadi bukan disebut milyarder lagi alias turun pangkat.